Selfie Dulu Baru Hidup
Redaksi - Tuesday, 17 February 2026 | 09:00 AM


Antara Eksistensi dan Obsesi: Ketika Selfie Bukan Lagi Sekadar Hobi, Tapi Penjara Digital
Bayangkan skenario ini: Kamu lagi nongkrong di kafe estetik yang baru buka di daerah Jakarta Selatan. Kopi sudah tersaji, lengkap dengan latte art yang rapi banget. Tapi, alih-alih menyeruput kopi selagi hangat, hal pertama yang kamu lakukan adalah merogoh kantong, mengeluarkan ponsel, dan mulai mencari sudut paling pas. Satu foto? Jelas nggak cukup. Kamu butuh setidaknya dua puluh jepretan dengan berbagai kemiringan kepala yang berbeda. Sepuluh menit kemudian, kopi sudah dingin, tapi kamu masih sibuk milih filter di aplikasi editing supaya kulit kelihatan lebih glowing daripada masa depan. Selamat datang di era di mana "selfie dulu baru makan" sudah jadi ritual wajib yang nggak tertulis.
Fenomena ini bukan hal baru, tapi belakangan ini levelnya sudah mulai bergeser dari sekadar dokumentasi jadi semacam adiksi. Kalau dulu kita foto bareng-bareng buat kenang-kenangan, sekarang fokusnya cuma satu: diri sendiri. Muncul istilah "Selfitis" yang pertama kali dilempar sebagai candaan, tapi belakangan mulai diseriusi oleh para peneliti perilaku. Pertanyaannya, kapan sih hobi narsis ini berubah jadi gangguan yang bikin kita capek sendiri?
Dopamin dalam Bentuk Tombol 'Like'
Kenapa sih kita susah banget berhenti selfie? Jawabannya ada di kepala kita, tepatnya di sistem penghargaan otak. Setiap kali kamu posting foto selfie yang menurutmu paling cakep, lalu muncul notifikasi "Like" atau komentar "Cakep banget sih!", otak kamu bakal ngelepasin dopamin. Zat kimia ini bikin kita merasa senang, puas, dan—yang paling berbahaya—ketagihan. Kita jadi haus akan validasi dari orang luar, seolah-olah nilai diri kita ditentukan oleh berapa banyak jempol yang mampir di kolom notifikasi.
Masalahnya, validasi digital itu sifatnya sementara banget. Hari ini kamu dipuji, besok kalau postinganmu sepi, kamu bakal merasa ada yang salah sama penampilanmu. Inilah yang bikin orang terus-terusan memproduksi selfie. Mereka bukan lagi mendokumentasikan hidup, tapi lagi "menambang" pengakuan. Efeknya? Kita jadi nggak pernah puas. Selalu ada sudut yang kurang tirus, hidung yang kurang mancung, atau pencahayaan yang kurang dramatis.
Perangkap Filter dan Krisis Identitas
Dulu, kalau mau kelihatan cakep, kita harus dandan maksimal. Sekarang? Cukup geser filter ke arah kanan, dan taraaa! Jerawat hilang, mata jadi lebih besar, dan dagu jadi lebih lancip secara ajaib. Teknologi filter ini sebenarnya pedang bermata dua. Di satu sisi, seru-seruan aja. Tapi di sisi lain, ini menciptakan standar kecantikan yang nggak masuk akal bahkan buat pemilik wajahnya sendiri.
Banyak anak muda sekarang yang merasa insecure justru setelah mereka melihat foto mereka sendiri yang sudah difilter habis-habisan. Ketika mereka bercermin di dunia nyata, mereka kaget melihat "versi asli" yang nggak se-estetik versi digital. Muncul istilah Snapchat Dysmorphia, di mana orang merasa perlu melakukan prosedur medis atau operasi plastik supaya wajah asli mereka mirip sama filter favorit mereka. Ini kan sebenarnya ironis banget. Kita jadi benci sama realitas gara-gara terlalu sering tinggal di dunia simulasi yang kita buat sendiri.
Kehilangan Momen demi Konten
Pernah nggak sih kamu pergi ke konser atau tempat wisata indah, tapi kamu malah sibuk ngatur posisi HP buat selfie membelakangi pemandangan? Kamu ada di sana secara fisik, tapi pikiranmu ada di layar ponsel. Kamu sibuk mikirin caption apa yang paling pas supaya kelihatan deep atau effortless, sampai-sampai kamu lupa menikmati hembusan angin atau suara musik yang lagi dimainin di depan mata.
Kecanduan selfie seringkali membuat kita kehilangan koneksi dengan realitas. Kita jadi terlalu sibuk mengkurasi hidup agar terlihat sempurna di mata orang lain, padahal aslinya kita mungkin lagi merasa hampa atau sendirian. Kita menciptakan narasi yang palsu. Foto lagi ketawa lebar sama teman-teman, padahal kenyataannya setelah tombol jepret ditekan, semuanya balik sibuk main HP masing-masing dan nggak ada obrolan yang berkualitas. Kita jadi aktor dalam film kehidupan kita sendiri, tapi penontonnya adalah orang asing di internet yang sebenarnya nggak terlalu peduli-peduli amat sama kita.
Memutus Rantai Obsesi
Terus, apakah kita nggak boleh selfie sama sekali? Ya boleh dong, nggak usah kaku-kaku amat. Masalahnya bukan pada kegiatannya, tapi pada tujuannya. Kalau selfie dilakukan buat seru-seruan atau sekadar pengingat "eh gue pernah di sini", itu sah-sah saja. Yang bahaya adalah ketika selfie jadi satu-satunya sumber kepercayaan diri kita. Ketika kamu merasa harimu hancur cuma gara-gara nggak ada foto yang "layak posting", itu tandanya kamu perlu digital detox sebentar.
Cobalah untuk sesekali pergi ke suatu tempat tanpa harus memamerkannya. Nikmati kopimu selagi panas. Lihat matahari terbenam dengan mata kepala sendiri, bukan lewat lensa kamera ponsel. Belajar buat nerima kalau wajah kita nggak selamanya simetris dan kulit kita punya pori-pori. Itu normal, itu manusiawi. Dunia nyata memang nggak punya tombol filter, tapi dunia nyata punya kedalaman rasa yang nggak akan pernah bisa ditangkap oleh sensor kamera 108 megapiksel sekalipun. Jadi, sebelum kamu pencet tombol kamera lagi, tanya ke diri sendiri: "Gue foto ini buat gue, atau buat mereka?"
Next News

FOMO, Scroll, Lelah: Siklus Setan Anak Internet
16 hours ago

Menjadi Turis di Negeri Sendiri
16 hours ago

Belajar Lewat Game: Efektif atau Cuma Gimmick
16 hours ago

Cerita Rakyat Indonesia: Antara Dongeng Moral dan Plot Absurd
16 hours ago

Hobi Receh yang Ternyata Bisa Jadi Cuan
17 hours ago
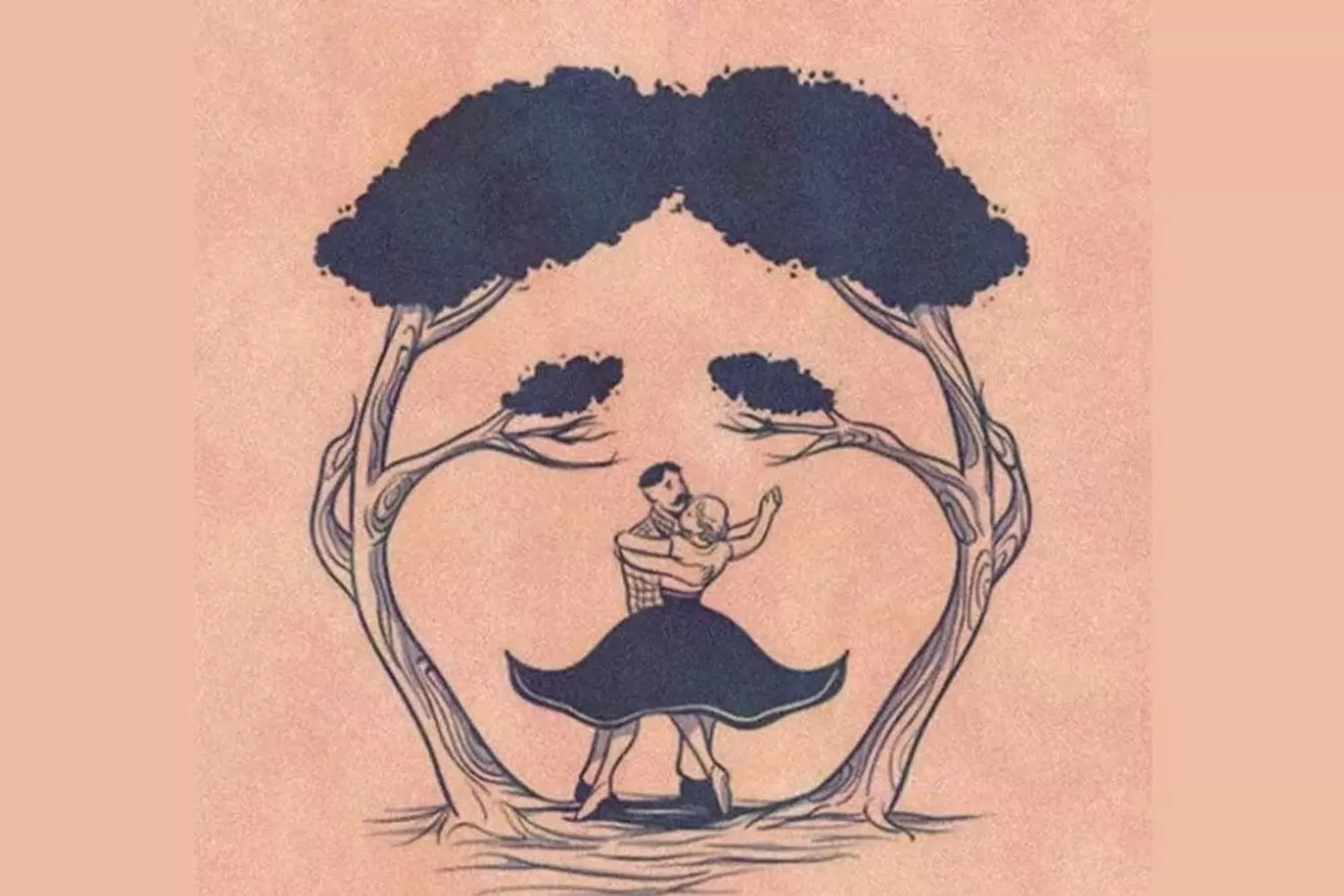
Yang Lo Lihat Belum Tentu Nyata
17 hours ago

Cara Tahu Orang Lagi Nggak Nyaman Tanpa Dia Bilang
17 hours ago

Psikologi Warna
18 hours ago

Sejarah Singkat: Kenapa Masa Lalu Itu Nggak Pernah Benar-Benar Lewat
18 hours ago

Otak: CEO Tubuh yang Kerjanya Gila-Gilaan Tapi Jarang Dihargai
18 hours ago





