Mak Ebun : Panggilan Kasih di Balik Kekuasaan Desa
Redaksi - Thursday, 30 October 2025 | 01:20 PM


Oleh : Faisol Ramdhoni
Di tanah garam yang kering dan berangin itu, hidup orang-orang yang keras dalam kerja, tapi lembut dalam rasa. Mereka punya caranya sendiri untuk menghormati, mencintai, dan memuliakan. Di Madura, panggilan sayang bisa ditujukan bukan hanya untuk ibu, melainkan juga untuk pemimpin. Sebutan itu adalah Mak Ebun.
Bagi telinga luar, Mak Ebun mungkin terdengar seperti nama panggilan kepada seorang ibu desa. Namun di balik bunyinya yang sederhana, tersimpan filosofi sosial yang dalam. "Mak" adalah seruan penuh kasih kepada seorang emak, tempat pulang dan berlindung. Sedangkan "Ebun" berasal dari akhiran kata klebun, sebutan Madura bagi kepala desa.
Maka ketika dua kata itu bertemu, "Mak Ebun" bukan lagi sekadar gelar administratif, tapi panggilan cinta yang mengandung rasa hormat, keibuan, dan pengayoman.
Dalam pandangan orang Madura, pemimpin bukanlah sosok yang harus ditakuti, tapi orang yang harus dihormati seperti orang tua sendiri. Karena itulah, klebun di mata masyarakat bukan sekadar pejabat, melainkan bagian dari empat figur sakral dalam tatanan hidup mereka: Buppa', Babbu', Guru, ban Rato : Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin.
Dalam konteks kehidupan desa, rato itu adalah klebun. Maka ketika seseorang memanggil "Mak Ebun", sebenarnya ia sedang menempatkan sang kepala desa di posisi luhur yang penuh kasih, seolah berkata: "Engkau bukan hanya pemimpin kami, tapi juga penjaga hati kami."
Pemimpin di Madura hadir bukan hanya di kantor, tapi di setiap denyut kehidupan warganya. Mislanya, ketika dua keluarga berselisih, Mak Ebun-lah yang pertama didatangi. Saat ada sengketa warisan, ia duduk di tengah, menjadi penenang di antara dua pihak yang bergejolak. Masyarakat mempercayakan semua prosesnya kepada Mak Ebun, dari awal sampai akhir.
Bahkan , ada keyakinan yang tidak tertulis: bila urusan sudah dipegang Mak Ebun, pasti akan ada jalan yang damai. Karena bagi mereka, Mak Ebun tidak hanya menandatangani surat, tapi juga menandatangani ketenangan di dada orang-orang desa.
Ketaatan seperti itu sering disalahpahami oleh orang luar sebagai bentuk feodalisme. Padahal bagi masyarakat Madura, itu adalah ketaatan yang lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Mereka tahu, dunia hanya bisa seimbang bila setiap orang tahu caranya menghormati. Mereka menghormati bukan karena kalah, tapi karena paham bahwa kehormatan adalah cara tertinggi manusia menjaga martabatnya.
Dalam budaya Madura, rasa hormat itu bukan perintah, tapi kebutuhan. Dan Mak Ebun adalah salah satu simpul tempat rasa hormat itu berlabuh.Karena itulah, ketika pemilihan kepala desa tiba, suasananya bukan sekadar urusan politik, tapi juga upacara sosial yang penuh makna.
Pilkades di Madura bukan hanya soal siapa yang menang, melainkan tentang siapa yang paling pantas dihormati. Untuk menjadi calon klebun, seseorang harus punya tiga bekal utama: kemampuan pribadi, jaringan sosial yang kuat termasuk kekerabatan dengan para blater atau tokoh pengaruh lokal dan kemampuan ekonomi.
Namun semua itu hanya pintu masuk. Yang paling menentukan sejatinya bukan berapa uang yang dimiliki, tapi seberapa dalam cinta masyarakat kepadanya. Sebab panggilan "Mak Ebun" tidak bisa dimenangkan di bilik suara; ia hanya bisa dimenangkan di hati rakyat.
Sebab iyu, suhu politik pilkades di Madura sangat tinggi, karena bukan hanya sekadar perebutan gelar. Itu pula sebabnya isu penundaan pilkades menjadi bola panas yang terus bergulir dan membangkitkan kegaduhan.
Dalam pilkades, yang dipertaruhkan bukan hanya kursi, melainkan juga kehormatan keluarga, gengsi sosial, dan wajah kepemimpinan di mata masyarakat. Tak jarang, pilkades menjadi ajang pembuktian tentang siapa yang benar-benar layak dipanggil Mak Ebun, bukan dalam arti hukum, tapi dalam arti rasa.
Pemimpin yang disebut Mak Ebun bukanlah yang duduk tinggi di kursi, tapi yang mau duduk rendah di tikar bersama warganya. Ia tidak hanya memerintah, tapi mendengarkan. Ia bukan sosok yang berjarak, melainkan yang hadir di tengah rakyat: di sawah, di langgar, di hajatan, di pemakaman. Ia adalah tempat orang-orang pulang, tempat orang kecil menaruh harap, tempat anak muda belajar menundukkan kepala tanpa merasa hina.
Di bawah bimbingan Mak Ebun, kekuasaan berubah wajah — dari instruksi menjadi nasihat, dari perintah menjadi pelukan. Memang, di Madura, pemimpin yang baik harus memiliki jiwa ibu. Itulah mengapa panggilan "Mak" disematkan di depan kata "Ebun".
Dalam jiwa keibuan itulah seorang pemimpin diharapkan bisa mengasuh warganya: menegur dengan sabar, mengingatkan dengan lembut, marah tanpa menyakiti, dan mengadili tanpa mempermalukan. Sebab bagi orang Madura, mempermalukan seseorang di depan umum lebih berat dosanya daripada kesalahan itu sendiri. Maka Mak Ebun belajar menegakkan aturan tanpa mencederai perasaan.
Madura adalah tanah yang keras. Batu kapur di bukitnya putih menyilaukan, anginnya kering, dan lautnya kadang ganas. Tapi di balik kekerasan alam itu, manusia Madura membangun kelembutan sosialnya sendiri. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara agar hidup tidak retak adalah dengan menumbuhkan kasih sayang di antara mereka. Maka meski keras bekerja, keras bicara, dan keras memegang prinsip, mereka lembut dalam hubungan. Itulah mengapa pemimpin bagi mereka bukan sosok yang tinggi dan jauh, tapi yang dekat dan menenangkan yakni Mak Ebun.
Zaman kini bergerak cepat. Jalan tol membelah Madura, gawai menggantikan surat, dan berita menyebar lebih cepat dari angin. Tapi di banyak desa, nilai-nilai lama masih berdenyut hangat. Di kantor desa yang kini berdinding keramik dan berpendingin udara, tetap ada kursi bambu di sudut ruang, tempat orang tua duduk menunggu giliran bicara pada Mak Ebun. Mereka masih datang dengan baju lusuh, membawa berkas dalam plastik bening, tapi yang mereka cari bukan tanda tangan melainkan ketenangan hati setelah didengarkan.
Mak Ebun bukan simbol masa lalu, tapi wajah kekuasaan yang manusiawi. Ia menunjukkan bahwa memimpin tidak harus berarti menaklukkan, tapi menenangkan. Bahwa menjadi pemimpin bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu menyayangi. Dan rasa sayang itu nyata: dalam senyum ketika warga datang mengadu, dalam kesabaran mendengar keluh yang sama dari orang yang sama, dalam langkah kaki yang tak segan menempuh rumah paling pinggir demi silaturahim.
Dalam dunia yang semakin dingin oleh perhitungan, Mak Ebun adalah pengingat bahwa masyarakat masih butuh kehangatan. Bahwa kekuasaan tanpa rasa tidak akan menumbuhkan apa pun kecuali jarak. Dan orang Madura, dengan seluruh kerasnya hidup, menolak hidup dalam jarak. Mereka lebih suka menjaga hubungan, menautkan hati dengan hati, meski lewat panggilan sederhana yang hanya terdiri dari dua kata tapi mampu menampung seluruh makna kemanusiaan: Mak Ebun.
Selama panggilan itu masih hidup di lidah rakyat, selama pemimpin masih disapa dengan bahasa kasih, maka Madura akan tetap menjadi tanah yang kuat dan teduh sekaligus. Sebab di sana, kepemimpinan bukan tentang perintah, tapi tentang pengasuhan. Bukan tentang jabatan, tapi tentang kepercayaan. Dan orang-orang yang hidup di bawah naungan kasih Mak Ebun tahu, bahwa kekuasaan sejati bukan berada di kursi, tapi di hati yang mau mendengar dan mencintai.
Dan karena itulah, ketika sebuah desa kehilangan sosok Mak Ebun yang definitif, maka desa itu kehilangan ruhnya. Kehilangan penuntun yang meneduhkan. Tidak ada lagi tempat berkeluh yang bisa menenangkan, tidak ada lagi suara lembut yang mampu menengahi amarah. Desa tanpa Mak Ebun ibarat tubuh tanpa jiwa, tetap berdiri, tapi tak lagi hidup dengan tenteram. Sebab bagi orang Madura, ketenangan bukan datang dari peraturan, melainkan dari kehadiran. Dan kehadiran itulah yang bernama: Mak Ebun.
Next News
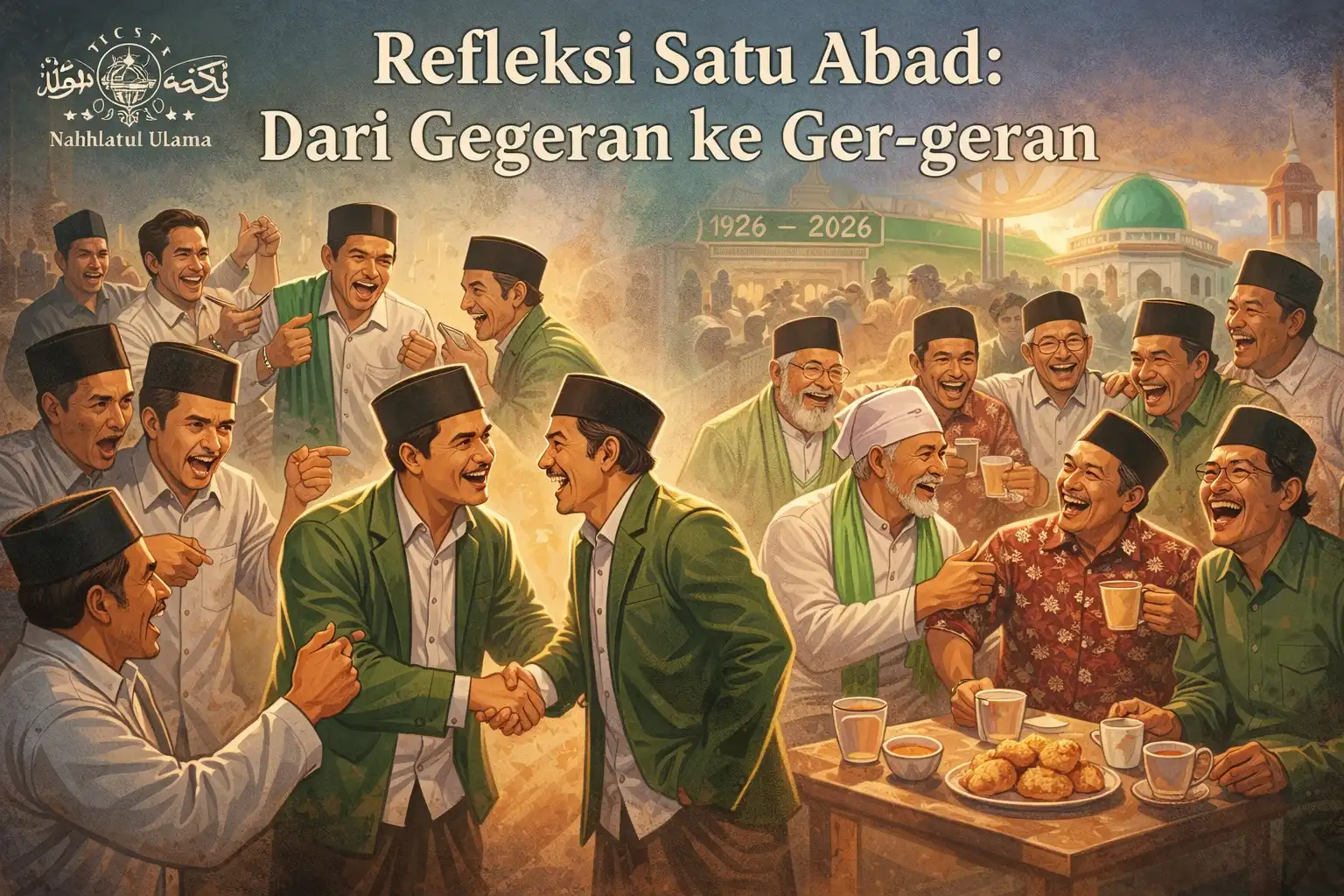
REFLEKSI SATU ABAD NU: DARI GEGERAN KE GERGERAN
a month ago

Madura dan Musik Dangdut
a month ago

Kronologis Bara Isu Pilkades Sampang: Dari Penundaan hingga Aksi Ricuh di Tahun 2025
3 months ago

Mimpi yang Menjadi Nisan
4 months ago

Kambing Hitam
5 months ago

Pecahnya Bisul Kemarahan Rakyat
5 months ago

Catatan Reflektif Historiografi Sampang :Dari Polagan, Roomtengah Hingga Pasedahan Banyuanyar
5 months ago

Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Pendidikan
6 months ago

Santri Jangan Patah Semangat, Belajar Pada Ibnu Hajar
6 months ago

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bukan Tanggung Jawab Satu Pihak
7 months ago





