Madura dan Musik Dangdut
Redaksi - Saturday, 20 December 2025 | 10:09 AM


Dangdut, seperti hidup itu sendiri, jarang menawarkan keindahan yang rapi. Ia tidak hadir dengan janji kesempurnaan, tidak pula dengan kemewahan teknis yang mengilap. Ia datang dengan suara yang kadang sumbang, cengkok yang berlebihan, dan lirik yang berulang-ulang. Namun justru di sanalah ia menemukan tempatnya. Dangdut hidup dari keseharian—dari kerja yang melelahkan, dari cinta yang patah sebelum sempat utuh, dari rindu yang tak selalu menemukan alamat pulang. Barangkali itu sebabnya ia bertahan. Ia tidak menuntut kekaguman, hanya pendengaran yang jujur.
Survei Skala Survei Indonesia pada 2022 mencatat dangdut sebagai genre paling diminati masyarakat Indonesia, dengan persentase 58,1 persen. Angka ini jauh melampaui musik pop, musik daerah, bahkan genre-genre yang sering diasosiasikan dengan selera "maju" dan "terdidik". Statistik semacam ini sering dibaca sepintas—sekadar data preferensi hiburan. Padahal, di balik angka-angka itu tersimpan peta sosial yang lebih dalam: tentang siapa yang berbicara, siapa yang didengar, dan suara mana yang dianggap sah untuk mewakili pengalaman kolektif.
Dangdut bekerja bukan hanya sebagai musik, melainkan sebagai bahasa. Andrew Weintraub, dalam Dangdut: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia, menyebut dangdut sebagai praktik sosial yang ikut membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan etnisitas di Indonesia modern. Ia bukan sekadar cermin realitas, tetapi turut membentuk cara masyarakat memandang dirinya sendiri. Dengan kata lain, dangdut adalah arsip hidup—yang menyimpan luka, harapan, kegagalan, dan negosiasi identitas yang sering tak mendapat ruang dalam wacana resmi.
Namun arsip ini tidak pernah sepenuhnya netral. Dangdut kerap dilekatkan pada kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Data SSI menunjukkan bahwa peminat terbesarnya berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan sekolah dasar, disusul SMP dan SMA, sementara lulusan perguruan tinggi berada di posisi paling rendah. Semakin tinggi pendidikan, semakin menurun tingkat kesukaan pada dangdut. Temuan ini kerap dibaca secara simplistik, seolah-olah dangdut adalah musik yang harus ditinggalkan seiring naiknya jenjang pendidikan.
Padahal, barangkali yang terjadi bukanlah penurunan selera, melainkan perubahan cara mengakui selera. Ada musik yang boleh didengarkan terang-terangan, dan ada yang cukup dinikmati diam-diam. Dangdut sering masuk kategori kedua. Ia dekat, tetapi tidak selalu ingin diakui. Ia dinikmati, tetapi jarang dibanggakan. Dalam situasi seperti inilah dangdut menemukan paradoksnya: ia mayoritas, tetapi sering merasa minor.
Di titik inilah Madura menjadi menarik. Pulau ini—yang kerap dilihat dari luar sebagai keras, miskin, dan tertinggal—menemukan dirinya dalam dangdut. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai pengakuan. Catatan-catatan riset tentang dangdut terasa klop dengan kondisi sosial Madura. Jika survei nasional itu diperdalam dan dikhususkan pada masyarakat Madura, besar kemungkinan angkanya akan melonjak jauh. Bukan karena masyarakat Madura menutup diri dari genre lain, melainkan karena dangdut berbicara dengan bahasa yang mereka pahami: lugas, emosional, dan tidak bertele-tele.
Dalam peta besar dangdut Indonesia, Madura kerap hadir tanpa gegap gempita. Ia jarang menjadi pusat sorotan industri hiburan, tidak rutin mencetak juara lomba televisi, dan tak selalu hadir dalam percakapan tren media sosial. Namun justru di situlah letak kekuatannya. Dangdut Madura tumbuh di jalur sunyi—jalur non-kompetisi, jalur panggung nyata, jalur kerja panjang yang tidak selalu tercatat kamera. Ia hidup di hajatan, di orkes keliling, di kaset pita yang berpindah tangan, dan di pengeras suara desa.
Kecintaan masyarakat Madura terhadap dangdut sesungguhnya tidak selalu membutuhkan pembuktian statistik. Ia hadir dalam hal-hal kecil yang berulang, yang justru karena kesehariannya sering luput dicatat. Dalam berbagai lomba karaoke yang digelar untuk memperingati hari-hari besar—dari tingkat desa hingga komunitas perantau—para peserta biasanya dibebaskan memilih genre lagu. Di titik kebebasan itulah dangdut hampir selalu menang. Bukan karena ada aturan tak tertulis, melainkan karena pilihan itu datang secara alamiah, seolah tubuh dan suara telah lebih dulu tahu ke mana harus berpihak.
Fenomena serupa dapat ditemukan di ruang-ruang yang lebih privat, yang cahaya dan sorotannya tidak sekeras panggung. Di bilik-bilik karaoke yang remang, dangdut kembali mengambil alih suasana. Ketika denting kendang dan cengkok khas itu terdengar, sering kali tak perlu menebak terlalu jauh: hampir bisa dipastikan, orang Maduralah yang sedang bernyanyi di dalamnya. Dangdut menjadi semacam penanda kultural—bukan simbol yang dipamerkan, melainkan kebiasaan yang dijalani tanpa perlu disadari.
Di ruang-ruang itu, dangdut tidak berfungsi sebagai tontonan, melainkan sebagai ruang pengakuan. Ia dipilih bukan untuk menunjukkan selera, melainkan untuk merasa dekat dengan diri sendiri. Lagu-lagu itu memberi kesempatan bagi penyanyinya untuk bersuara penuh, tanpa harus menyesuaikan diri dengan standar keindahan yang kerap ditentukan dari luar. Dalam dangdut, suara boleh keras, emosi boleh tumpah, dan cerita boleh berlebihan. Semua itu justru dianggap wajar.
Dangdut Madura tidak berhenti di pulau asalnya. Ia ikut bergerak bersama orang-orang Madura yang merantau ke berbagai wilayah Jawa Timur, bahkan menembus batas negara. Di kalangan diaspora, khususnya komunitas Tenaga Kerja Indonesia, dangdut Madura menjadi pengikat identitas dan pelepas rindu. Musik ini hadir dalam acara komunitas, pertemuan kekeluargaan, hingga ruang digital lintas negara—sebuah cara sederhana untuk pulang, meski tubuh tetap jauh.
Secara historis, dangdut Madura tidak lahir secara tiba-tiba. Konon, embrionya berakar pada kesenian Al Badar Lesbumi yang berkembang sejak era 1960-an, dirintis oleh Mukri, seorang pengurus Nahdlatul Ulama yang aktif di Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia. Dari perpaduan seni religi, rakyat, dan musik pertunjukan itulah lahir identitas musikal yang kemudian dikenal sebagai dangdut Madura Situbondoan. Sejak awal, ia sudah bersifat inklusif dan adaptif.
Secara musikal, dangdut Madura menyerap banyak pengaruh: musik India dan Arab, pop Barat, pop Indonesia, hingga tradisi lokal seperti Kendang Kempul Banyuwangi, Campursari Jawa, dan Gendhing Madura. Bahkan unsur disko Barat pun sempat hadir dalam beberapa aransemen. Perpaduan ini menunjukkan satu hal penting: budaya tidak pernah statis. Ia selalu bergerak, menyerap, dan bernegosiasi dengan perubahan, tanpa harus kehilangan akar.
Dalam lintasan sejarah non-kompetisi ini, nama-nama seperti Yus Yunus dan Imam Arifin menjadi penanda penting. Mereka lahir dari panggung nyata—tanpa juri, tanpa voting, tanpa legitimasi industri besar. Yang menentukan bertahan atau tidak hanyalah suara, rasa, dan ketahanan mental. Penonton Madura dikenal keras dan jujur. Penyanyi yang goyah akan tersingkir dengan sendirinya. Seleksi alam berlangsung ketat, tetapi adil.
Karakter vokal Madura yang kuat, emosional, dan lugas menjadi keunggulan di panggung nyata. Namun ketika masuk ke format televisi—yang menuntut kerapian, durasi singkat, dan standar selera nasional—karakter ini sering dianggap terlalu liar. Bukan karena kualitasnya rendah, melainkan karena tidak mudah diseragamkan. Televisi menyukai yang bisa dipadatkan; panggung Madura menyukai yang bisa bertahan lama.
Meski demikian, Madura tidak sepenuhnya absen dari jalur kompetisi. Dalam ajang pencarian bakat dangdut, muncul nama-nama seperti Irwan DA, Sherly Madyana, Andi Prasetia, hingga generasi lebih muda seperti Valen Akbar. Di luar televisi, ruang digital membuka jalur baru yang lebih longgar. Penyanyi-penyanyi seperti Firdaus Sanjaya, M. Halili, Lusyana Jelita, dan Ardea Annafianti membangun karier melalui kerja panjang, bukan sensasi sesaat.
Di antara seluruh peta itu, Fildan Rahayu menempati posisi unik. Kemenangannya di D'Academy Asia 2015 bukan anomali. Ia adalah produk ekosistem Madura: kuat vokal, tahan mental, dan terbiasa menyanyi panjang. Ia tidak dibentuk oleh kompetisi, tetapi menguji dirinya melalui kompetisi. Fildan menjadi jembatan lintas era—menghubungkan tradisi panggung hajatan dengan televisi dan dunia digital.
Pada akhirnya, dangdut Madura menunjukkan bahwa seni tidak selalu harus berlomba untuk bernilai. Ia bisa berjalan dengan iramanya sendiri—setia pada rasa, jujur pada panggung, dan sabar menunggu waktu. Dalam dunia yang semakin tergesa-gesa oleh viralitas dan kompetisi, Madura menawarkan pelajaran penting: bahwa kesetiaan pada proses sering kali lebih menentukan daripada kemenangan sesaat.
Dan ketika akhirnya dangdut Madura bersinar, kilau itu bukan kebetulan. Ia adalah hasil perjalanan panjang yang telah ditempa jauh sebelum kamera menoleh ke arahnya—di panggung-panggung kecil, di suara-suara yang tak selalu direkam, dan di rasa yang tetap bertahan, meski dunia berubah.
Next News
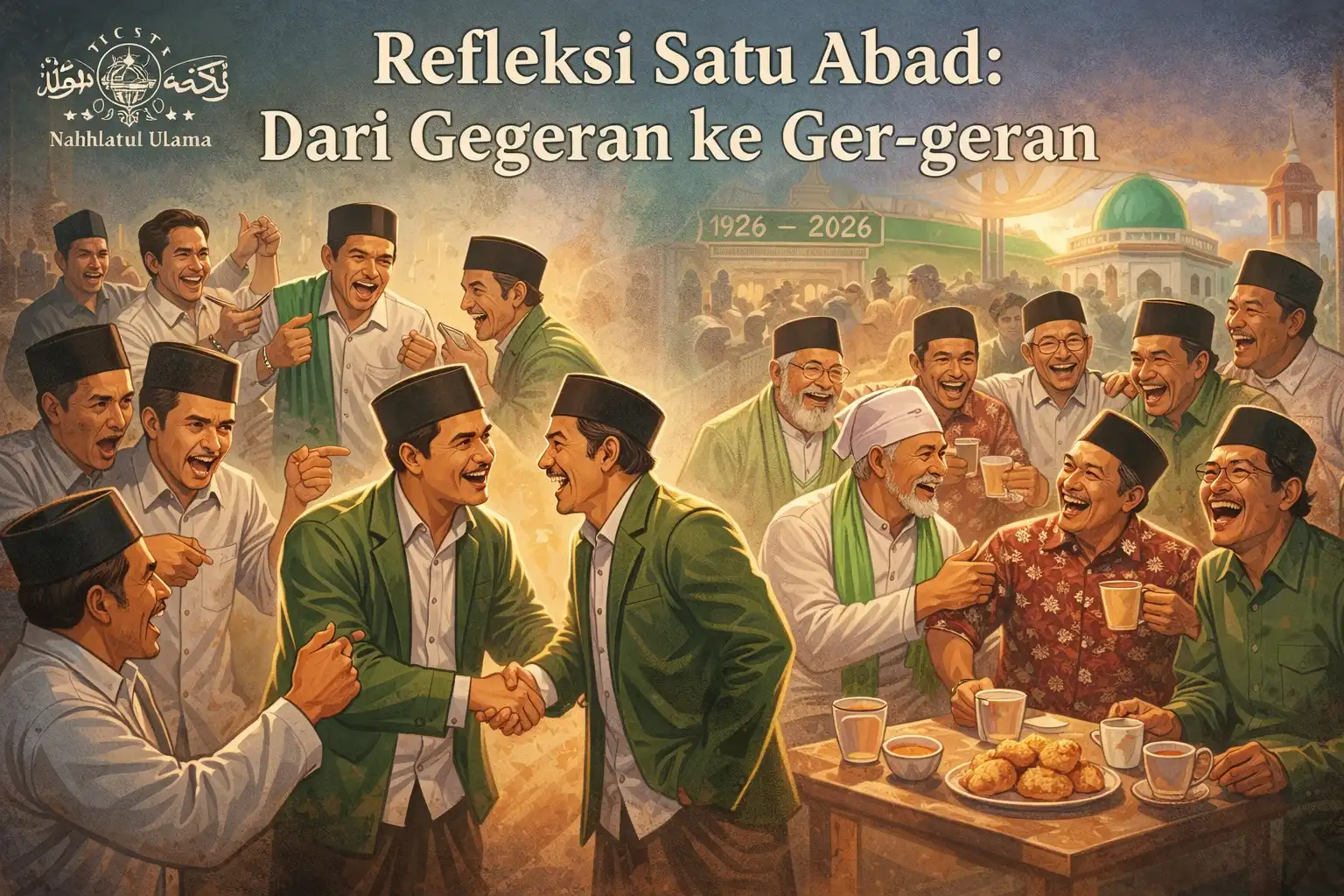
REFLEKSI SATU ABAD NU: DARI GEGERAN KE GERGERAN
a month ago

Kronologis Bara Isu Pilkades Sampang: Dari Penundaan hingga Aksi Ricuh di Tahun 2025
3 months ago

Mak Ebun : Panggilan Kasih di Balik Kekuasaan Desa
3 months ago

Mimpi yang Menjadi Nisan
4 months ago

Kambing Hitam
5 months ago

Pecahnya Bisul Kemarahan Rakyat
5 months ago

Catatan Reflektif Historiografi Sampang :Dari Polagan, Roomtengah Hingga Pasedahan Banyuanyar
5 months ago

Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Pendidikan
6 months ago

Santri Jangan Patah Semangat, Belajar Pada Ibnu Hajar
6 months ago

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Bukan Tanggung Jawab Satu Pihak
7 months ago





