Tiga Surat Dari Prapen
Redaksi - Wednesday, 09 July 2025 | 06:11 PM


Oleh: Faisol Ramdhoni*
Malam Jumat, Malam 1 Muharram. Hujan turun rintik sejak Sore, tidak deras, tapi cukup menghapus jejak-jejak debu di jalan setapak menuju Makam Sunan Prapen. Di antara pohon-pohon tua dan akar-akar yang melilit tanah, Abdullah berjalan pelan, membawa mushaf yang telah usang di tangan kanan, sajadah di tangan kiri, dan luka yang tak pernah benar-benar sembuh dalam dadanya.
Sudah lima tahun sejak badai menerjang rumah tangganya. Istrinya pergi, anak-anaknya dibawa jauh, dan sejak itu Abdullah tinggal sendiri di rumah kecilnya di pinggir kota. Waktu berjalan, tapi sepi tak pernah berlalu. Ia memilih datang ke tempat ini bukan untuk mencari ketenangan, tapi untuk menyerahkan seluruh resahnya kepada langit.
Di tanah yang basah oleh zikir dan napas para auliya, Abdullah berniat menyempurnakan khatam Al-Qur'an dalam tiga malam sunyi.
Malam turun pelan seperti kelambu. Udara di kompleks makam semakin basah, dan suara jangkrik mulai menggantikan langkah-langkah manusia yang telah pulang dari ziarah. Abdullah masih di sana, duduk bersila di bawah pohon sawo tua yang daunnya gemetar setiap kali angin berhembus pelan. Di hadapannya, mushaf telah terbuka, lampu kecil menyala temaram, dan sajadah telah menyerap doa-doa sejak maghrib.
Satu per satu ayat ia baca. Kadang suaranya terdengar utuh, kadang gemetar, dan kadang ia terdiam lama di tengah ayat, seolah ada yang sedang ia tahan di dada.
Setelah menyelesaikan sepuluh juz pertama, ia menyandarkan punggung pada batu nisan tanpa nama. Udara malam semakin dingin, tapi yang membuat tubuhnya menggigil bukan angin, melainkan bayangan wajah anak-anaknya yang muncul satu per satu di pelupuk mata.
Tangannya gemetar membuka lembaran kertas kusam. Ia mulai menulis. Perlahan, dengan jeda di setiap baris, seolah tiap kalimat adalah panggilan rindu yang selama ini hanya bisa dipendam dalam sujud
Malam Pertama – Juz 1–10
Surat Pertama
Untuk anak-anakku yang tumbuh jauh dari pelukan Ayah, tapi tidak pernah jauh dari doa…
Jika surat ini kalian baca entah kapan, di antara tumpukan buku sekolah, atau dalam sunyi malam saat kalian sendiri, ketahuilah: Ayah menulisnya dalam keadaan sepi, tapi tidak kosong. Ayah menulisnya setelah membaca sepuluh bagian awal dari kitab yang telah lama Ayah tinggalkan, lalu Ayah peluk kembali malam ini dengan air mata dan rindu yang tak bisa disebut dengan kata-kata.
Anak-anakku, Al-Qur'an dibuka dengan permintaan paling mendasar manusia: tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka jangan pernah malu merasa bingung. Bingung itu pertanda hati masih mencari. Ayah pun pernah tersesat, dalam urusan dunia, dalam ego, bahkan dalam cinta. Tapi malam ini Ayah belajar lagi: meminta petunjuk bukan tanda kelemahan, tapi justru kekuatan paling jujur dari seorang hamba.
Bani Israil banyak bertanya, dan justru tersesat oleh pertanyaan mereka sendiri. Kadang, terlalu banyak analisa bisa menutupi rasa. Maka belajarlah untuk tunduk tanpa kehilangan akal. Sebab iman tak harus selalu dijelaskan—ia cukup dijaga.
Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengubah arah kiblat. Maka jika nanti hidup kalian tiba-tiba berubah arah—jangan mengira Allah sedang menghukum. Mungkin Dia sedang menyelamatkan.
Di surat Ali Imran, Ayah membaca kisah Uhud. Betapa sahabat Nabi pun bisa kalah. Tapi kekalahan itu menjadi pelajaran yang membuat mereka lebih kuat. Jadi jangan takut gagal. Gagal adalah cara Allah membentuk hati yang lebih lapang.
Dan anak-anakku, jangan berharap semua orang akan menerima kebaikanmu. Para nabi pun ditolak. Kalian tidak sedang menjual jasa. Kalian sedang menjaga nurani. Dan nurani hanya butuh satu hal: keikhlasan.
Surah An-Nisa' mengajarkan bahwa adil bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Cinta yang tidak adil, akan melukai. Maka belajarlah mencintai dengan menjaga. Jaga diri, jaga lisan, jaga marah, jaga sabar.
Ayah tahu, kalian tumbuh tanpa peluk Ayah. Tapi jika nanti kalian dewasa, dan kalian jatuh cinta, dan suatu hari rumah tangga kalian diuji seperti Ayah dulu, ingatlah Surah Al-Maidah—bahwa seberat apa pun luka, Allah selalu membuka pintu taubat.
Dan jika kalian kecewa karena tidak segera dibalas dalam doa, lihatlah kisah Musa yang bertahun-tahun berjalan sebelum Fir'aun tumbang. Allah tidak tergesa. Dia hanya memilih waktu yang paling tepat.
Ayah ingin kalian tahu, bahwa para nabi bukan manusia super. Mereka takut, mereka ragu, mereka kadang lelah. Tapi mereka tahu satu hal: Allah tidak pernah tidur. Maka jika kalian letih, berhentilah sebentar. Tapi jangan pergi dari-Nya.
Anakku, malam ini Ayah kembali belajar berjalan. Bersama ayat-ayat yang dulu sering kita dengar saat tadarusan bersama di bulan Ramadan. Sekarang Ayah membacanya sendirian. Tapi Ayah percaya, suara ini akan sampai ke kalian, suatu hari, entah lewat angin, mimpi, atau ayat yang kalian baca tanpa sengaja.
Dan saat kalian membaca surat ini—jika suatu saat hidup kalian kacau, hati kalian sempit, atau iman kalian nyaris padam—bukalah kembali Juz pertama. Di sana, Ayah menitipkan doa yang tak sempat Ayah bisikkan di telinga kalian saat kalian kecil.
Dengan cinta yang tidak akan habis meski waktu habis,
Ayahmu,Yang menulis dari tanah yang basah oleh zikir
Malam kedua datang dengan hening yang lebih dalam. Setelah Isya, Abdullah kembali ke tempat duduknya semula di bawah pohon sawo, membawa mushaf dan selembar kertas baru. Udara lebih lembap dari malam sebelumnya, dan kabut turun perlahan dari perbukitan utara. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara lirih dan hati yang mulai pasrah. Dan ketika bacaan telah sampai pada penghujung juz kedua puluh, ia menutup mushaf, memejamkan mata sejenak, dan kembali menulis surat. Tangannya mulai terbiasa, tapi isi hatinya tetap saja penuh—rindu yang belum sempat ia ucapkan.
Malam Kedua– Juz 11–20
Surat Kedua
Anak-anakku tersayang…
Jika surat sebelumnya adalah tentang langkah-langkah pertama dalam perjalananmu bersama Al-Qur'an, maka kini izinkan Ayah menuntunmu menembus lembar-lembar tengah yang lebih dalam—dari juz sebelas hingga dua puluh—di mana ruhmu mulai diuji, hatimu mulai ditimbang, dan hidupmu mulai memijak tanah pilihan-pilihan yang lebih berat.
Di Juz 11, ada surah Yusuf yang tak pernah habis dibicarakan oleh para pencinta. Bukan semata karena ketampanan Nabi Yusuf, tapi karena ketampanan sabarnya. Dikhianati saudara, difitnah oleh kekuasaan, dipenjara karena menolak maksiat, tapi Yusuf tidak pernah membalas. Maka belajarlah dari Yusuf, Nak. Bahwa indah bukan karena wajah, tapi karena jiwa yang tetap jernih meski dicelup dalam lumpur. Bahwa keberhasilan bukan soal dipuji manusia, tapi diterima oleh Tuhan.
Masuk ke surah Ar-Ra'd dan Ibrahim, kita diajak mengenal makna keteguhan. Bahwa pohon iman itu akarnya menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Nak, dunia ini akan mengajakmu jadi pohon plastik: mengilap, tapi tidak hidup. Tapi Ayah ingin kalian jadi pohon yang benar-benar hidup—meski akarnya harus menembus tanah luka, meski daunnya digugurkan musim-musim cobaan.
Di surah Al-Hijr, Allah menegaskan, "Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami pula yang menjaganya." Ayah membaca ini sambil gemetar. Betapa kasih sayang Allah menjaga ayat-ayat-Nya agar tetap bisa kita baca hari ini. Maka jangan hanya membaca Al-Qur'an, Nak. Biarkan pula Al-Qur'an membaca kita. Jangan hanya hafalkan ayat, tapi biarkan hidupmu jadi ayat yang dihafalkan langit.
Juz 15 hingga 16 memperkenalkan kita pada an-Nahl—sang Lebah. Allah puji makhluk kecil ini karena ia hidup dengan hikmah. Ia bekerja dalam diam, membangun rumah-rumah dari ketaatan. Nak, jadilah seperti lebah: ia hinggap di bunga, tapi tak pernah merusaknya. Ia menyimpan racun, tapi tak menyakiti. Ia mengeluarkan madu, bahkan saat disakiti. Dunia butuh lebih banyak lebah, dan lebih sedikit lalat.
Lalu datanglah surah Al-Isra', surah perjalanan agung dari bumi ke langit—Mi'raj. Tapi lihatlah, perjalanan itu dimulai dari sujud. Nak, jangan pernah anggap remeh sholatmu. Mungkin gajimu kecil, mungkin duniamu sempit, tapi siapa tahu sujudmu malam ini sedang menumbuhkan taman-taman tak terlihat yang akan menyelamatkanmu kelak. Sujudlah, bahkan jika yang kau tangisi hanya kegagalan kecil—karena Allah besar dalam perkara sekecil apapun.
Surah Al-Kahfi—di Juz 15–16 juga—menyampaikan pesan untuk para pemuda. Tentang anak-anak muda yang melarikan diri bukan karena takut dunia, tapi karena ingin mempertahankan iman. Nak, jika nanti teman-temanmu mengajakmu menjauh dari jalan Allah, ingatlah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Mereka tak takut dianggap aneh. Karena menjadi benar dalam dunia yang salah, memang akan selalu terasa sepi.
Lalu di surah Maryam dan Thaha, kita bertemu kembali dengan Musa dan Isa. Tapi ada satu ayat yang membuat Ayah terdiam lama: saat Musa berkata, "Rabbi syrahli shadri…"—"Ya Allah, lapangkanlah dadaku." Nak, jika kelak kamu tak kuat, mintalah kelapangan, bukan keringanan. Karena hidup tak selalu bisa dibuat ringan, tapi dada kita bisa diperluas oleh sabar dan ridha.
Juz 17 hingga 18 dihiasi oleh surah Al-Anbiya dan Al-Hajj. Kisah para nabi diabadikan bukan karena mereka tanpa luka, tapi karena mereka tetap mencintai Allah meski dilukai. Lihat Ibrahim dibakar, lihat Nuh ditertawai, lihat Zakariya tak kunjung dikaruniai. Tapi tak satu pun dari mereka berhenti berdoa. Nak, jangan ukur cintamu kepada Tuhan dari seberapa cepat doa dikabulkan. Ukurlah dari seberapa kuat engkau tetap percaya bahkan ketika semua terasa diam.
Lalu Juz 19 dan 20, kita mulai merasakan aura perang batin yang lebih dalam. Surah Al-Mu'minun misalnya, memulai dengan kalimat yang menenangkan: Qad aflaha al-mu'minun—beruntunglah orang-orang beriman. Tapi coba lihat siapa mereka? Bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling rajin ceramah, tapi mereka yang khusyuk dalam sholatnya, yang menjauh dari yang sia-sia, yang menjaga janji dan amanah. Nak, keberuntungan sejati tidak ada di aplikasi investasi atau peluang viral. Ia ada dalam ketundukan batin yang tak terlihat.
Surah An-Nur datang sebagai cahaya. Allah menyebut diri-Nya: Allahu nuru as-samawati wal-ardh—Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka jika hidupmu terasa gelap, jangan cari cahaya di luar dulu. Carilah Allah, dan biarkan Dia menyalakan lentera di dadamu. Jaga pandanganmu, jaga kehormatanmu, karena cahaya tidak bersahabat dengan hati yang kotor.
Anak-anakku…
Surat ini bukan tentang hafalan. Ini tentang arah. Tentang bagaimana kalian berjalan dalam dunia yang makin gaduh dan penuh tipu daya. Jika kalian kehilangan Ayah, kehilangan tempat bertanya, kehilangan pijakan… jangan kehilangan Al-Qur'an. Di dalamnya ada suara-suara yang lebih lembut dari bisikan Ayah. Ada cahaya yang lebih terang dari lampu mana pun. Ada pelukan yang lebih dalam dari segala rindu.
Ayah tak tahu berapa lama lagi bisa menulis seperti ini. Tapi selama kalian membaca ayat demi ayat dengan hati yang terbuka, kalian akan selalu menemukan Ayah—dalam getar huruf-huruf yang kalian lafalkan, dalam diam yang kalian resapi setelah doa, dalam sujud yang kalian benamkan di malam-malam sepi.
Teruslah berjalan. Langkahmu mungkin goyah, tapi jangan biarkan hatimu berbalik arah. Karena jalan pulang masih panjang, dan Allah sedang menunggu di ujungnya.
Dengan cinta yang tak berkesudahan,
Ayahmu, yang hanya ingin kalian selamat dunia akhirat.
Malam terakhir datang seperti angin yang mengabarkan perpisahan. Abdullah menyadari bahwa setiap lembar yang ia baca malam ini adalah pamungkas dari perjalanan batinnya. Sejak Maghrib, ia duduk lebih lama menatap langit, mengingat kembali bagaimana tiga malam ini telah membersihkan ruang-ruang jiwanya yang kusut.
Ketika surah-surah pendek mulai terdengar di bibirnya, air mata pelan-pelan turun tanpa suara. Dan seperti dua malam sebelumnya, setelah bacaan selesai, ia mengambil selembar kertas terakhir. Tapi kali ini ia menulis bukan hanya dengan rindu, melainkan dengan keikhlasan. Inilah surat penutup, yang ia tulis dengan tangan yang gemetar tapi dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya.
Malam Terakhir– Juz 21–30
Surat Ketiga
Anak-anakku yang Ayah cintai…
Kita telah sampai di ujung. Lembar-lembar Al-Qur'an sudah makin tipis, tapi justru di situlah hikmah kian padat. Seperti akhir perjalanan yang tak hanya menuntut tenaga, tapi juga niat yang murni dan keyakinan yang utuh. Juz 21 sampai 30 bukan hanya penutup bacaan, tapi pernyataan cinta dari langit—yang dititipkan langsung ke dada manusia.
Di Juz 21, kalian akan bertemu surah Al-Ankabut. Tahukah kalian, Allah membandingkan rumah orang-orang yang bergantung pada selain-Nya dengan rumah laba-laba—rapuh dan mudah terbang oleh angin. Nak, dunia ini menawarkan banyak sandaran, banyak pelarian. Tapi jangan biarkan hatimu menggantung di benang-benang rapuh. Sandarkan hidupmu pada Zat yang tidak pernah goyah.
Lanjut ke surah Ar-Rum, kita belajar bahwa kemenangan dan kekalahan hanyalah bingkai dari pelajaran iman. Manusia bergembira karena dunia, tapi Allah mengingatkan: kemenangan sejati bukan saat engkau unggul di mata manusia, tapi ketika engkau tetap bersujud meski dunia menyudutkanmu.
Lalu di surah Luqman, Ayah tak tahan untuk tidak menitikkan air mata. Karena di sana ada nasihat seorang ayah kepada anaknya. Sama seperti surat ini. Luqman berkata, "Wahai anakku, dirikanlah sholat, perintahkan yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah." Nak, jika kelak Ayah tiada, bacalah ayat itu sebagai pengganti nasihat yang tak sempat Ayah ulang-ulang.
Kemudian kalian akan temui surah Sajdah, surah yang menceritakan mereka yang menangis di malam hari. Jangan takut pada air mata, Nak. Tangisanmu di malam yang sunyi, bisa jadi lebih nyaring di langit daripada seribu orasi. Allah tahu siapa yang diam-diam menunduk, saat yang lain tertawa keras-keras di pesta dunia.
Surah Yasin—jantung Al-Qur'an—ada di Juz 22. Di sanalah kalian akan temui kebenaran disampaikan oleh seorang lelaki biasa, dari pelosok kota. Bukan ulama besar. Bukan bangsawan. Tapi ia berkata, "Ikutilah mereka yang tak meminta imbalan dan berada di jalan yang lurus." Nak, jadilah seperti dia. Tak perlu panggung besar untuk menegakkan kebenaran. Satu suara kecil yang ikhlas, bisa mengguncang takdir.
Di Juz 23 dan 24, kalian akan berjumpa dengan surah Az-Zumar dan Ghafir. Di sana, Allah memperkenalkan Diri-Nya sebagai Zat yang membuka pintu taubat seluas-luasnya. Bahkan untuk dosa yang seluas samudera. Maka Nak, jangan pernah merasa terlalu rusak untuk kembali. Bukan dosamu yang besar, tapi rasa malumu yang kadang kecil. Allah tak menolak pendosa. Yang Ia tolak hanya mereka yang sombong untuk bertobat.
Surah Fussilat datang membawa gambaran tentang orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," lalu mereka istiqamah. Ayah selalu berdoa, semoga kalian bisa istiqamah. Bukan dalam tampilan luar, tapi dalam kedalaman hati. Dunia akan mencoba menarik kalian ke kanan-kiri, tapi tetaplah tegak—karena yang tegak tidak selalu tinggi, tapi pasti kuat.
Juz 26 dan 27 menyapa lewat surah Asy-Syu'ara dan An-Naml. Di sana ada Musa, ada Harun, ada Sulaiman, ada burung Hud-hud yang menyampaikan berita iman. Nak, jangan remehkan suara kecil dalam dirimu. Bisa jadi bisikan hati yang kau anggap kecil, justru datang dari langit. Dengarkan ia. Kadang malaikat datang dalam bentuk kesadaran yang sangat sederhana.
Kemudian surah Al-Qashash mengingatkan bahwa Musa dulu hanya bayi hanyut, tapi Allah menyiapkan takdir besar baginya. Jangan pernah remehkan dirimu, Nak. Kau mungkin merasa kecil, tapi siapa tahu kau sedang digendong oleh takdir, menunggu waktu untuk bangkit dan membawa cahaya.
Surah Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, dan selanjutnya, mengalir hingga Juz 28 dan 29—dengan surah Al-Mulk yang menjadi pelindung kubur, surah Al-Qalam yang menjaga akhlak, surah Al-Haqqah yang menggambarkan kedahsyatan hari akhir, dan surah Al-Ma'arij yang menuntun kesabaran menanjak ke langit.
Dan akhirnya kita tiba di Juz 30.
Juz terakhir ini seperti embun. Pendek-pendek ayatnya, tapi mengandung samudera. Di sinilah surat-surat yang kita hafal sejak kecil berada: Al-Fil, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas. Tapi jangan anggap kecil ayat-ayat ini. Justru di sinilah Allah menyusun pelindung-pelindung paling kokoh bagi hati manusia.
Surah Al-'Asr menyampaikan bahwa manusia rugi, kecuali mereka yang beriman, beramal shalih, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nak, jika kalian tak sempat hafal ratusan ayat, cukuplah kalian hidup dalam makna Al-'Asr. Karena waktu yang hilang tak bisa dibeli kembali, dan amal yang sia-sia tak bisa diganti dengan pujian.
Surah terakhir, An-Naas, mengajarkan kita bahwa musuh terbesar bukan di luar, tapi dalam dada. Bisikan-bisikan kecil, yang menumbuhkan iri, sombong, marah, putus asa—itulah iblis yang paling lihai. Maka Ayah ingin kalian belajar berlindung. Bukan hanya dari bahaya di luar, tapi dari huru-hara di dalam jiwa.
Anak-anakku…
Kini kita telah menuntaskan mushaf ini bersama. Tapi Al-Qur'an bukan buku yang tamat setelah dibaca. Ia adalah jalan pulang. Bacalah ia berulang kali, karena setiap kali kau membacanya, sebenarnya kau sedang membacamu sendiri—membaca siapa dirimu, dari mana asalmu, dan ke mana akhirnya kamu akan kembali.
Ayah tak tahu berapa usia Ayah tersisa. Tapi andai ini adalah malam terakhir, maka biarkan ia menjadi penutup yang indah. Kalian tidak perlu membalas semua cinta Ayah. Cukup teruskan kebaikan, dan doakan Ayah saat kalian rindu.
Ayah percaya, Allah mempertemukan yang saling mencintai, meski terpisah oleh jarak, bahkan oleh kematian.
Dengan rasa cukup, dan cinta yang ingin membebaskan dan yang hanya ingin kalian pulang bersama cahaya.
Ayahmu
Yang menulis dari ujung malam, sebelum azan Subuh terakhir
Ahad pagi, Abdullah melipat mushafnya untuk terakhir kali. Ia mencium kertas usang itu, menyimpannya dalam tas, lalu berdiri. Tak ada yang menjemput, tapi hatinya seperti pulang membawa sesuatu yang telah lama hilang. Ia menuruni tangga makam perlahan, menyusuri jalan kecil yang kini kering oleh mentari pagi.
Di terminal gresik, Abdullah duduk menunggu bus antar kota. Tangannya masih memegang tiga lembar surat. Ia belum mengirimnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu: ketiga surat itu sudah sampai.
Bukan lewat pos. Bukan lewat ponsel. Tapi lewat langit, yang selalu terbuka bagi doa dan cinta yang tulus.
Next News
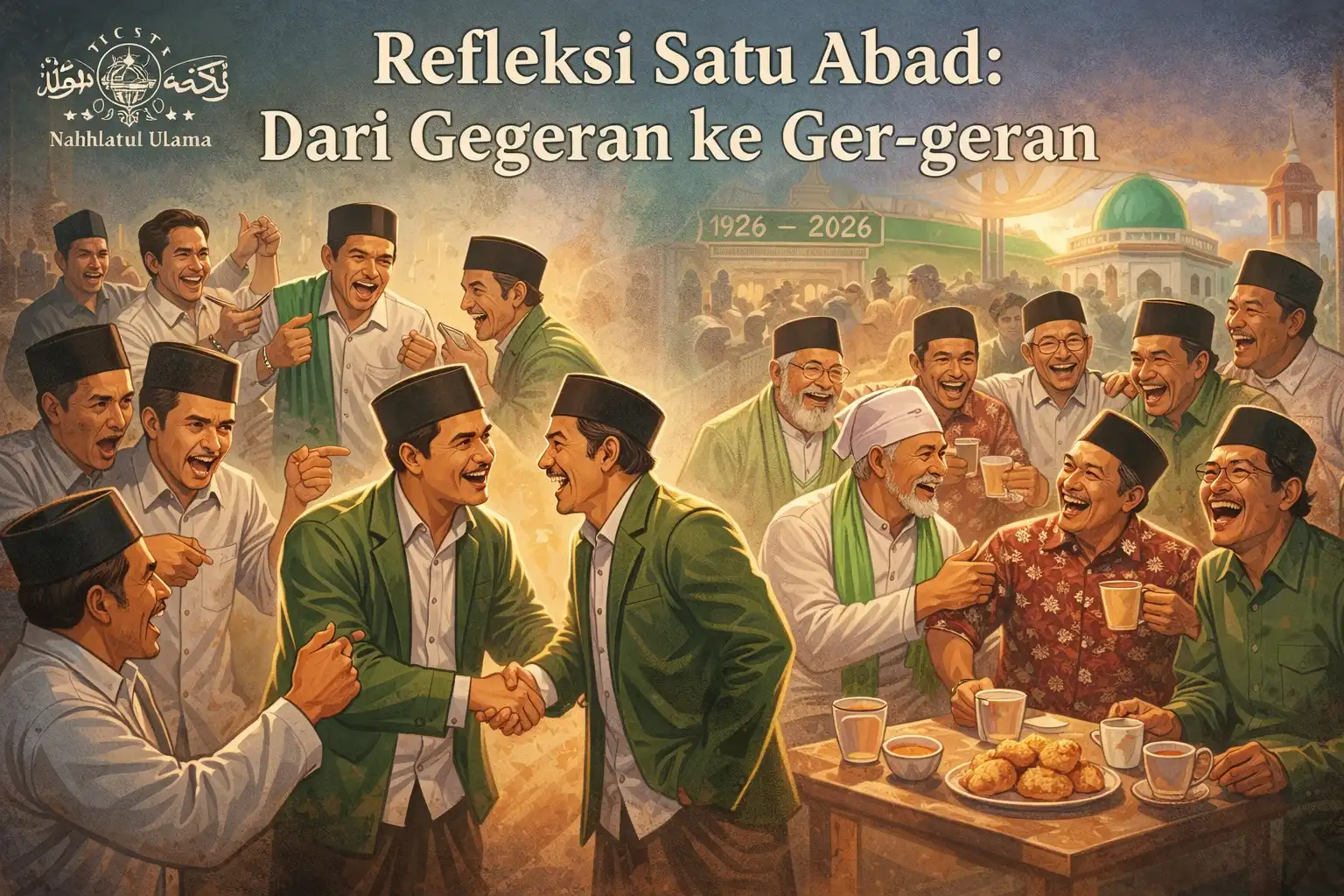
REFLEKSI SATU ABAD NU: DARI GEGERAN KE GERGERAN
2 months ago

Madura dan Musik Dangdut
3 months ago

Kronologis Bara Isu Pilkades Sampang: Dari Penundaan hingga Aksi Ricuh di Tahun 2025
4 months ago

Mak Ebun : Panggilan Kasih di Balik Kekuasaan Desa
4 months ago

Mimpi yang Menjadi Nisan
6 months ago

Kambing Hitam
6 months ago

Pecahnya Bisul Kemarahan Rakyat
6 months ago

Catatan Reflektif Historiografi Sampang :Dari Polagan, Roomtengah Hingga Pasedahan Banyuanyar
6 months ago

Kemerdekaan dan Tanggung Jawab Pendidikan
7 months ago

Santri Jangan Patah Semangat, Belajar Pada Ibnu Hajar
7 months ago





